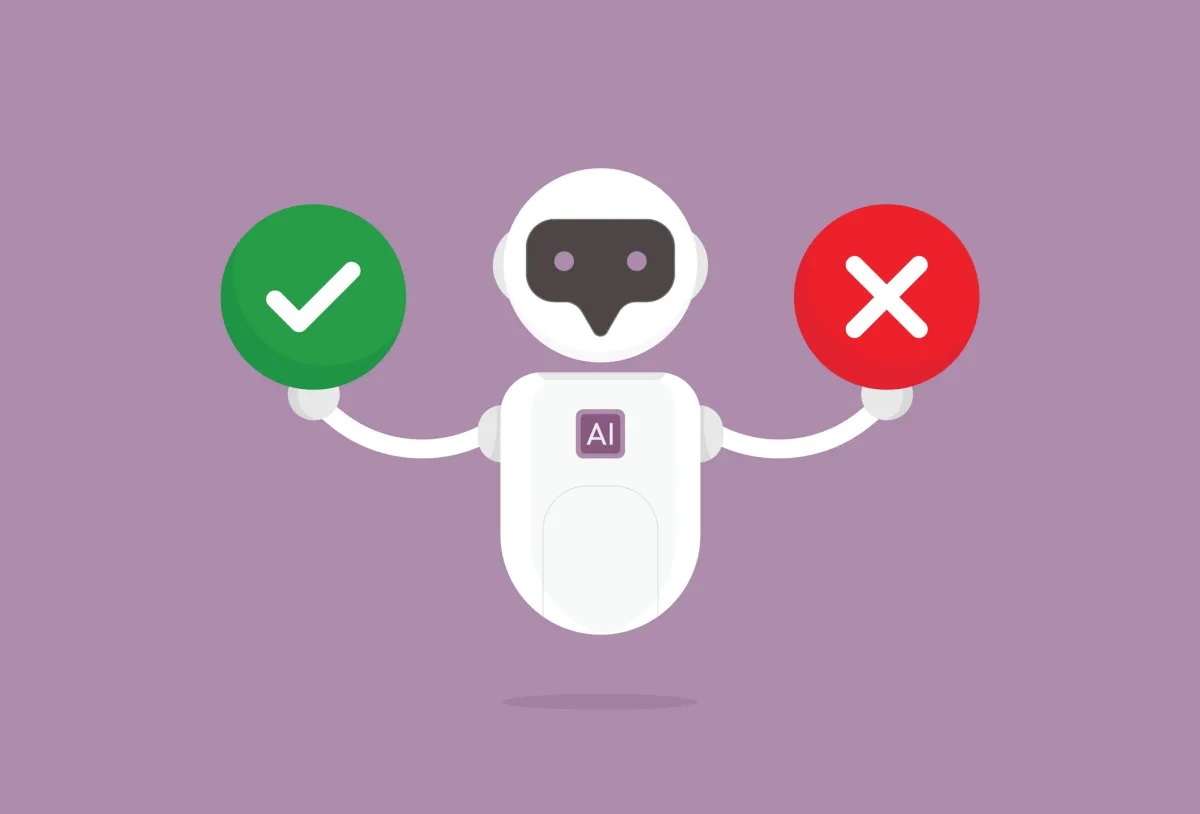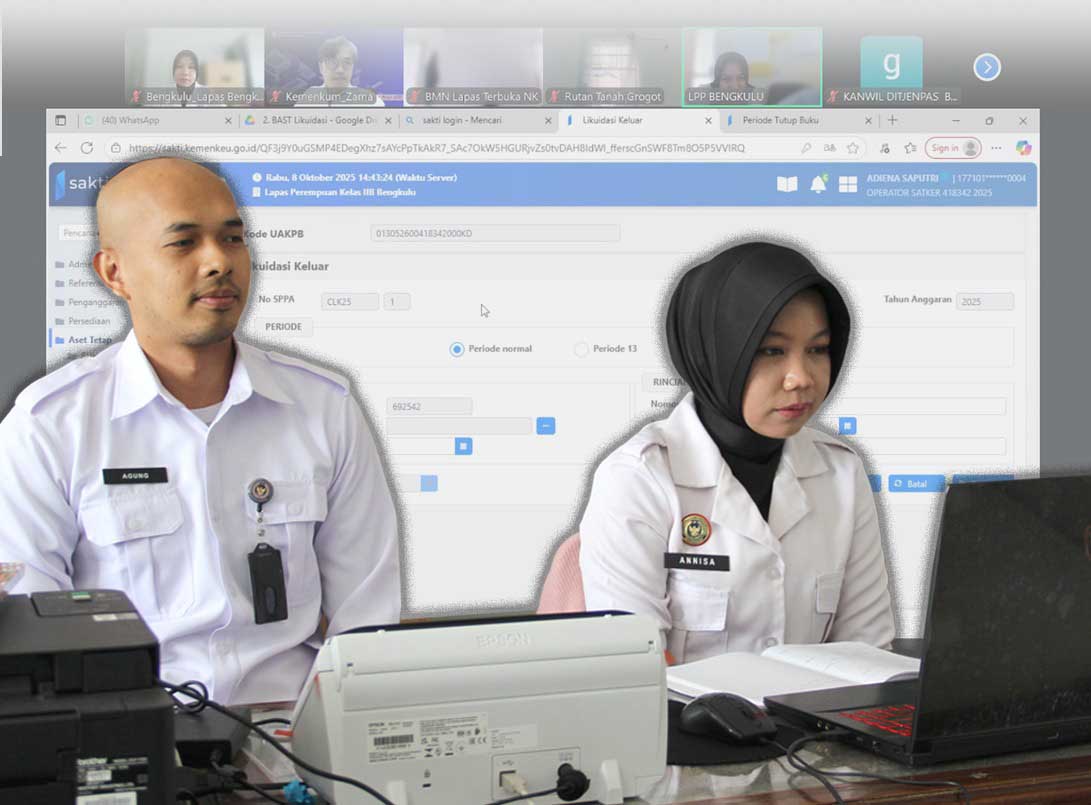Melintasi batas yang tak bisa dijangkau suara
Siapa yang Merawat Perempuan di Balik Kerja Kemanusiaan?
17 menit lalu
Sebanyak 60 persen pekerja perempuan di sektor sosial dan advokasi di Indonesia rentan mengalami burnout.
***
Saya kira dengan terus bergerak, semuanya akan reda. Tapi ternyata, beberapa hal tidak bisa disembuhkan dengan kesibukan.
Bak Tuhan, orang-orang hanya mengingatnya ketika mereka menghadapi cobaan hidup. Mungkin diriku pun begitu datang membawa perasaan sedih, marah, kecewa, dan malang, semua menyerbu bersamaan. Sudah lama perasaan itu tidak muncul serentak, dan kini ia kembali, mencari jalan keluar lewat tulisan.
Saya pikir saya sudah pulih. Tapi rupanya saya hanya pandai mengalihkannya dengan bekerja. Bekerja tanpa jeda, seolah semakin sibuk saya, semakin kecil kemungkinan hal-hal itu kembali menghampiri. Padahal justru di tengah kesibukan itu, sesuatu yang lama berdiam di dalam diri mulai mengetuk kembali.
Pulih, ternyata bukan akhir dari perjalanan, tapi proses yang terus diuji. Orang-orang datang menguji sejauh mana pulihmu bertahan. Tubuh dan pikiran menagih haknya untuk istirahat, tapi saya malah menegosiasikannya dengan kalimat yang sama: “Nanti saja, masih banyak yang harus dikerjakan.”
Beberapa bulan lalu saya harus dirawat karena sakit punggung. Dokter bilang otot saya menegang terlalu lama. Tapi setelah sembuh, saya kembali ke ritme yang sama: sembilan hari tanpa jeda, berpindah dari satu kegiatan di Bantaeng, Makassar ke Bantaeng naik motor, lalu ke tempat wisata menemani kawan-kawan, kemudian ke lokasi kegiatan selanjutnya semuanya dengan motor. Saya lupa membawa botol minum, jarang makan teratur, dan akhirnya Jumat malam tubuh saya tumbang.
Saat pulang ke rumah, saya berharap ketenangan. Tapi yang datang justru kalimat dari ibu, “Kata bapak, kapan anak bungsunya ini jadi PNS juga? Anak-anak kerabat semua sudah.”
Sial. Saya belum pandai menjelaskan pekerjaan yang saya cintai, tapi juga yang perlahan menggerus tenaga dan jiwa saya. Di desa, perempuan berpendidikan tinggi seperti saya masih diukur dari seberapa cepat menjadi PNS. Disituasi ini, saya benci jalannya dunia ini.
Malam itu punggung saya semakin sakit. Ibu juga yang datang membawa hot in cream. Tangannya yang keriput mengoleskannya ke punggung saya, menekan pelan sambil berbisik, “Jangan dipaksakan, Nak.” Esok paginya, ia datang lagi membawa sarapan, camilan, segelas air. Hal-hal kecil yang beberapa hari sebelumnya saya abaikan di luar sana.
Saya terdiam, menyadari bahwa bahkan di tengah tuntutan dan salah pahamnya, ibu tetap jadi sosok pertama yang merawat ketika tubuh dan hati saya menyerah.
Oh Ibu, maafkan anakmu ini yang hanya mengingat pulang ketika sudah sakit. Bukankah dulu saya berjanji akan kembali untuk merawatmu? Nyatanya, malah sebaliknya. Saya ingin dirimu hidup lebih lama, bukan agar kembali merawat saya, tapi agar saya sempat melihat kebahagiaanmu, dan semoga suatu saat peranmu akan terganti.
Di situlah saya sadar, di balik semua kerja kemanusiaan yang saya jalani, selalu ada seseorang yang diam-diam memastikan saya tetap hidup: ibu. Perempuan yang tak pernah bicara tentang advokasi, tapi setiap tindakannya adalah bentuk paling tulus dari perawatan dan cinta.
Esoknya saya berusaha menenangkan diri: membaca, meditasi, menggambar. Tapi semua terasa tumpul. Saya hanya melakukannya saat keadaan darurat, saat kepala saya berat, pikiran kosong, dan perasaan gelap itu datang tanpa aba-aba. Saya tahu, tubuh saya sedang menolak cara saya memperlakukannya: dengan memaksa.
Namun dari ibu, saya belajar bahwa merawat tidak selalu berarti menolong orang lain. Kadang, merawat berarti mengizinkan diri sendiri untuk berhenti, untuk diam, untuk merasakan. Bahwa yang merawat perempuan, sering kali juga perempuan lain dan pada akhirnya, diri perempuan itu sendiri.
Saya bekerja di lembaga yang bergerak di isu lingkungan dan advokasi, tempat orang-orang berbicara lantang soal “membela kaum tertindas.” Tapi akhir-akhir ini, saya mulai mempertanyakan eksistensi saya: sebagai perempuan yang juga punya keluarga, mau sampai kapan begini? Sebagai pegiat sosial sampai kapan saya sanggup? Ini bukan tentang imbalan, tapi tentang rasa kehilangan arah, tentang seseorang yang ingin menolong banyak orang, tapi lupa menolong dirinya sendiri.
Saya tahu, saya tidak sendiri. Laporan Magdalene tahun 2023 mencatat bahwa 60 persen pekerja perempuan di sektor sosial dan advokasi di Indonesia rentan mengalami burnout karena tekanan kerja dan ekspektasi sosial yang saling bertabrakan. Tekanan itu sering datang dari dua arah: dari publik yang menuntut konsistensi perjuangan, dan dari lingkungan pribadi yang mengharapkan peran domestik sempurna.
Dalam tulisan Anotasi (2024) berjudul “Activist Burnout: Ketika Aktivisme Melelahkan,” seorang penulis menulis: “Kadang, satu-satunya cara agar perjuangan tetap hidup adalah memberi kesempatan bagi diri untuk berhenti sejenak.” Kalimat itu menampar saya. Mungkin memang begitu: kadang berhenti bukan tanda menyerah, tapi cara tubuh memohon agar jiwanya tetap hidup.
Sore itu, saya keluar ke serambi rumah. Ayah sedang menjemur cokelat di atas terpal, ibu menata kacang dan pisang. Di belakang rumah, beberapa buah jagung diikat menjadi satu menggunakan tali dari pangkal klobotnya yang dipilin kuat hingga membentuk ikatan besar menjuntai dari atas ke bawah. Di pohon mangga, satu buah besar tampak kehitaman, bekas gigitan burung.
Saya teringat kata Aan Mansur, bahwa apa yang kita amati bisa menggambarkan apa yang sedang kita alami. Saat melihat buah mangga yang digigit burung itu, saya merasa melihat diri sendiri: ada bagian dari diri yang mulai membusuk karena terlalu lama dipaksa kuat.
Mungkin benar, memulihkan diri bukan tentang kembali seperti semula, tapi tentang mengenali kapan harus berhenti. Saya belajar bahwa aktivisme yang tidak memberi ruang untuk istirahat akan kehilangan jiwa kemanusiaannya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan luka orang lain, kalau kita sendiri belum selesai memulihkan diri?
Penulis Indonesiana
3 Pengikut

Siapa yang Merawat Perempuan di Balik Kerja Kemanusiaan?
17 menit lalu
Digitalisasi Kehidupan: Privasi, Kriminalisasi, & Konten Negatif Media Sosial
Minggu, 10 Agustus 2025 21:23 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0



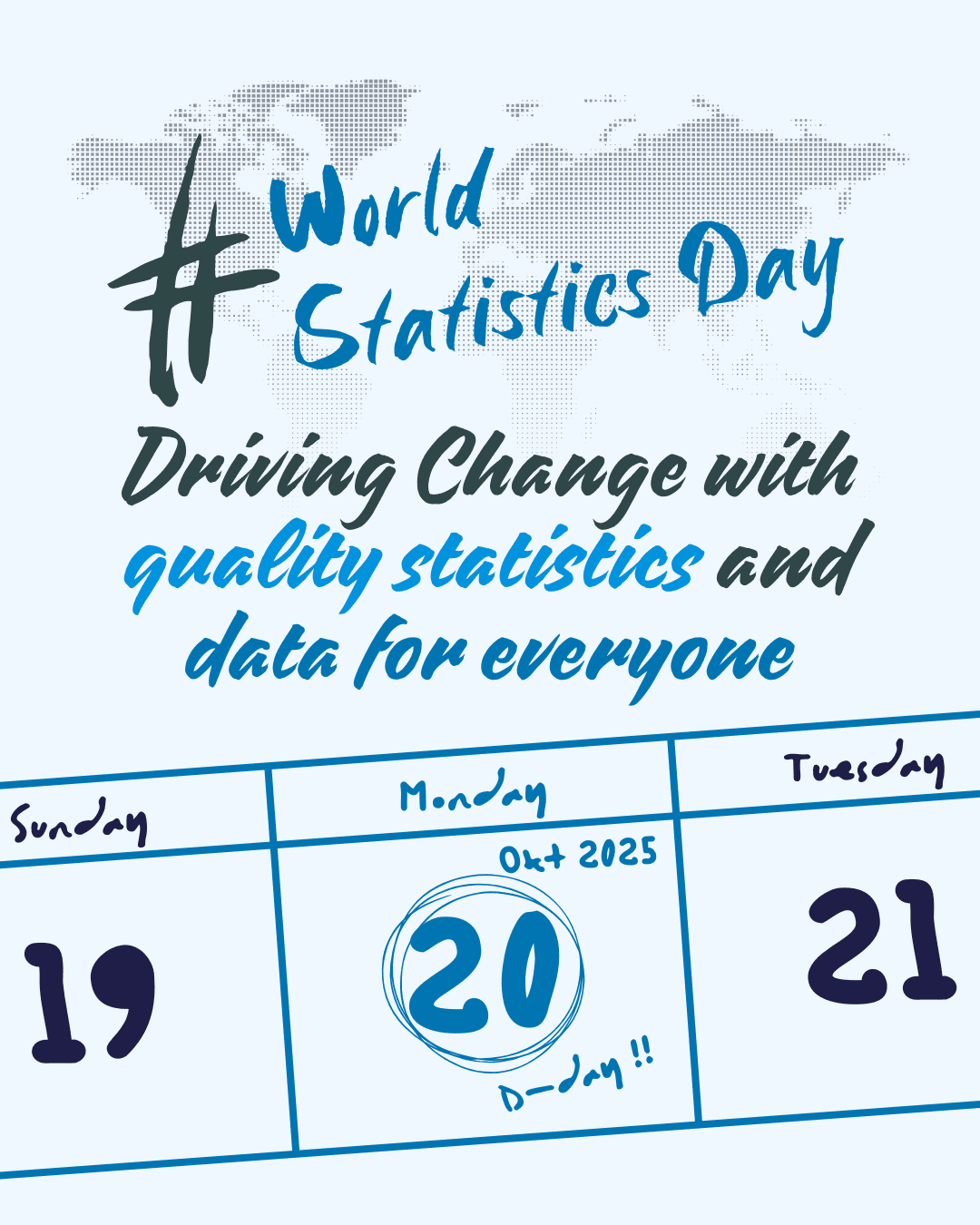


 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0